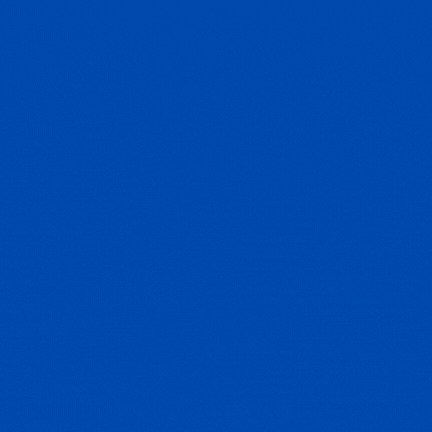Penulis: Tim Redaksi Pondok Pesantren Mansajul Ulum
Terbit pada: Kolom Jum'at Edisi ke 3
Di wilayah pantai utara, desa Kajen yang terletak di kabupaten Pati, Jawa Tengah, sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai desa santri.
Julukan ini tidak berlebihan karena sepertiga jumlah pesantren yang tersebar di wilayah kabupaten Pati berada di daerah Kajen dan sekitarnya. Pemandangan para santri dengan kostumnya yang khas, sarung, jilbab dan peci, menjadi pemandangan yang lumrah menghiasi sudut-sudut desa ini.
Suara pengajian, dzibaan, dan shalawatan, hampir setiap waktu bisa kita dengarkan dari gang-gang kampung tersebut.
Banyaknya pesantren di desa Kajen tidak bisa dilepaskan dari sosok kharismatik yang sangat dihormati masyarakat Kajen, yaitu Mbah Ahmad Mutamakin atau dikenal dengan Mbah Mutamakin.
Sosok kharismatik ini konon disangka sebagai sumber dan poros keilmuan pesantren Kajen. Karena hampir seluruh pengasuh pesantren yang ada di Kajen dan sekitarnya, bermuara pada nasab Mbah Mutamakin.
Kiai yang dikenal sebagai salah satu waliyullah ini bernama asal Sumohadiwijaya. Ayahnya bernama Sumohadinegoro, adalah pangeran Benowo II bin Pangeran Benowo I (R. Hadiningrat) bin Jaka Tingkir (R. Hadiwijoyo).
Beberapa referensi menceritakan adanya perbedaan pendapat mengenai jalur nasabnya. Sebagian mengatakan bahwa nasab Kiai Mutamakin ini bersambung sampai pada Raden Fatah dan Jaka Tingkir.
Tetapi adapula yang menyatakan bahwa nasabnya bersambung sampai pada Rasulullah melalui Abdurrahman Basyaiban ibn Sayyid Umar.
Terlepas dari perbedaan pendapat terkait nasab mbah Mutamakin, masyarakat Kajen meyakini bahwa Kiai Mutamakin setelah menikahi Nyai Qadimah, putri Mbah Syamsudin, Kajen, telah melahirkan beberapa putera dan putri.
Mereka adalah Raden Hendro Muhamad, Raden Bagus, dan Nyai Alfiah. Dari ketiga putra-puterinya ini lahirlah para ulama-ulama pengasuh pesantren yang tersebar di desa Kajen dan sekitarnya.
Dalam buku "Kisah Perjuangan Syekh KH. Ahmad Mutamakin, Kajen" yang ditulis oleh Bapak Sanusi dijelaskan bahwa Raden Bagus berkiprah di Jawa Timur. Sementara Nyai Alfiah atau dikenal dengan Nyai Godeg dan Raden Hendro Muhamad menetap di Pati.
Terdapat tiga poros besar pesantren Kajen yang muncul dari keturunan Mbah Mutamakin. Pertama adalah Pondok Pesantren Tengah yang mulanya didirikan oleh KH. Ismail, buyut Mbah Mutamakin pada abad ke-19. Pesantren ini kemudian dilanjutkan oleh KH. Fayumi Munji dan berubah menjadi Pesantren Raudhatul Ulum yang kini diasuh oleh KH. Isma’il Fayumi.
Kedua, adalah Pondok Kulon Banon yang diprakarsai oleh Mbah Nawawi yang kemudian berubah menjadi Taman Pendidikan Islam Indonesia (TPII) dan diasuh oleh Kiai Durri Nawawi.
Selanjutnya pesantren ini dibawah kepemimpinan keluarga Bani Thahir kembali Bernama Pesantren Kulon Banon (PKB) yang kini diasuh oleh KH. Muadz Thohir.
Ketiga, adalah Pondok Wetan Banon yang didirikan oleh KH. Sirodj pada tahun 1902 yang selanjutnya berubah menjadi pesantren Salafiyah.
Setelah tiga pesantren itu, mulailah bermunculan pesantren-pesantren lain. Seperti Pesantren Polgarut yang diprakarsai oleh KH. Abdussalam yang belakangan dilanjutkan oleh putra dan cucu-cucunya.
Di Polgarut sendiri terdapat dua pesantren tua, yaitu PMH Pusat yang diasuh oleh Mbah Abdullah Salam, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Nafi’ Abdillah dan berlanjut kepada putra-putrinya. Yang satu adalah PMH Putra yang didirikan oleh Mbah Mahfudz Salam lalu dilanjutkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh dan kini diasuh oleh KH. Abdul Ghaffar Rozin.
Tiga pesantren poros tersebut kemudian melahirkan banyak pesantren-pesantren baru yang tersebar di Pati.
Pesantren Kulon Banon dan Polgarut merupakan keturunan dari Mbah Hendro Muhamamad. Sementara Pesantren Tengah dan Wetan Banon konon berasal dari jalur keturunan Nyai Alfiah.
Selain dua pesantren tersebut, jalur nasab mbah Nyai Alfiah juga menurunkan beberapa pesantren, seperti Pesantren Mansajul Ulum, Cebolek Kidul, dan Pesantren Mamba’ul Ulum, Kajen.
Kedua Pesantren ini merupakan pesantren yang didirikan oleh keturunan dari Mbah Halimah, ibunda Mbah Muhammadun, Pondowan Tayu.
Berbicara tentang pesantren di Kajen yang memiliki muara keilmuan pada Mbah Mutamakin, maka kita perlu menelusuri genealogi keilmuan beliau.
Sebagaimana termaktub dalam buku "Syekh Mutamakin: Perlawanan Kultural Agama Rakyat" oleh Zainul Milal Bizawie, bahwa sanad keilmuan mbah Mutamakin disinyalir bermuara pada guru-gurunya yang berada di Timur Tengah.
Salah satu yang disebut dalam buku itu adalah Syekh Jen atau Syekh Zain bin Muhamad Abdul Baqi Al Mizaji yang berasal dari Yaman.
Syekh Jen sendiri dikenal sebagai sosok ahli tasawuf yang beraliran Naqsyabandiyah. Tetapi selain Syekh Jen, Kiai Mutamakin juga disinyalir berguru pada Syekh Yusuf Al Makassari dan Abdurrauf Al Sinkili.
Kita tahu nama terakhir adalah salah satu tokoh sufi nusantara yang beraliran falsafi. Ia mengajarkan paham martabat tujuh yang merupakan perpanjangan dari ajaran wahdatul wujud Ibnu Arabi.
Dugaan adanya persinggungan Mbah Mutamakin dengan aliran tasawuf falsafi ini menjadi sangat kuat ketika kita simak cerita yang terekam dalam Serat Cebolek tentang pengadilan yang hendak dilakukan oleh keraton Kartasura akibat desakan para ulama’ ‘fiqh’ yang dipelopori oleh Ketib Anom dari Kudus.
Pengadilan itu disebut-disebut akibat keberatan para ulama terhadap ajaran mistik Mbah Mutamakin yang disinyalir menyimpang dari Syariat. Salah satunya adalah lantaran ia memelihara dua anjing yang dalam mitologi masyarakat sekitar Kajen merupakan penjelmaan dari hawa nafsu Mbah Mutamakin.
Terlepas dari corak tasawuf yang dianut oleh Mbah Mutamakin, yang menarik dicermati dari sosok beliau adalah kemampuannya mentransformasikan ajaran-ajarannya kepada murid-murid dan masyarakat di sekitarnya.
Dalam rekaman Serat Cebolek, diceritakan bahwa Mbah Mutamakin ini menggunakan kisah Bhima Suci dalam menggambarkan ajaran hakikat. Kita tahu bahwa kisah Bhima Suci yang tergambar dalam Serat Dewa Ruci adalah cerita Pewayangan Jawa asli yang menggambarkan tentang pencarian terhadap air kehidupan.
Apresiasi Mbah Mutamakin terhadap serat Dewa Ruci ini menggambarkan penghargaan beliau terhadap ajaran budaya yang menjadi keyakinan masyarakat.
Oleh beberapa peneliti, Mbah Mutamakin disebut sebagai tokoh Neo-Sufisme yang mencoba menggabungkan antara tasawuf falsafi yang sangat teoritik dengan tasawuf akhlaqi yang berorientasi pada perbaikan akhlak, menjadi konsep tasawuf amaly.
Karena itu watak ajaran Mbah Mutamakin, sebagaimana disebut Milal, adalah kontekstual-transformatif. Ia mampu mengejawentahkan ajaran-ajaran tasawuf dalam kehidupan secara berdampingan dengan budaya lokal yang ada.
Selain itu, Mbah Mutamakin juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam melakukan perubahan pada masyarakat lokal.
Sikap itu ia wujudkan melalui upayanya yang kritis dalam menyikapi pandangan keagamaan keraton yang cenderung menggunakan label syari’ah sebagai kedok dalam melanggengkan kekuasaan politik.
Akibatnya, keraton sering mengabaikan hak-hak dan tuntuan rakyat demi melanggengkan kekuasaan kerajaan. Sikap inilah yang membangkitkan Mbah Mutamakin untuk melakukan perlawanan secara kultural. Salah satunya melalui penamaan kedua anjingnya dengan nama-nama yang sama dengan seorang penghulu dan katib di Tuban.
Penamaan itu disinyalir sebagai kesengajaan untuk melakukan sindiran terhadap nafsu serakah pemerintah dalam menghadapi rakyat jelata yang miskin.
Karakter keilmuan Mbah Mutamakin yang demikian itu telah mempengaruhi corak keilmuan para ulama-ulama Kajen.
Pesantren Kajen memiliki watak keilmuan yang cenderung berbeda dengan keilmuan pesantren salaf pada umumnya.
Meski pesantren Kajen mayoritas mengkaji kitab turats yang salaf, tetapi cara pandang pesantren terhadap kitab-kitab tersebut tidaklah tekstual.
Sebaliknya, mereka lebih berani membaca dan mentransformasikan kitab-kitab kuning itu secara kontekstual. Kontekstualisasi itu juga dilakukan dengan semangat penghargaan pada budaya dan kearifan lokal.
Sehingga agama mampu terserap dalam laku budaya masyarakat dan santri Kajen dengan baik. Yang terakhir adalah kemampuan pesantren untuk bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengkooptasi pesantren.
Hal itu telah ditunjukkan secara turun-temurun oleh para Kiai-Kiai dan para santri Kajen. Sosok-sosok itu misalnya bisa terbaca dari profil Mbah Mahfudh, Mbah Abdullah Salam, Kiai Sahal hingga para Gus-Gus muda sekarang ini.
Meski demikian, pesantren Kajen tetap mampu menjadi mitra pemerintah dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang baik demi kemaslahatan pesantren dan bangsa Indonesia.
Wallahu a’lam Bisshawab.